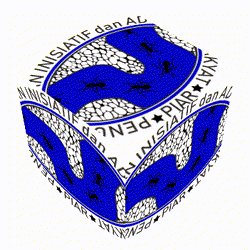OTONOMI DAERAH NTT: GURITA
KORUPSI DI DAERAH MISKIN
Kondisi
sebagian besar alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur boleh jadi tandus dan
gersang. Kekeringan dan rawan pangan seolah menjadi bencana rutin yang dihadapi
warga NTT hampir setiap tahun.
Kemiskinan,
kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta angka penganggur yang tinggi pada
akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu.
Kini, lebih
dari satu dekade pelaksanaan otonomi daerah, beban rakyat NTT semakin berat
karena pada saat yang sama harus menghadapi bencana baru yang muncul akibat
buruknya tata kelola pemerintahan daerah. Bencana yang sudah ada di depan mata
dan dipastikan makin memiskinkan rakyat NTT itu adalah korupsi.
Berdasarkan
pantauan Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT
sepanjang 2009 terhadap 16 dari 21 kabupaten/kota di NTT, ada 125 kasus dugaan
korupsi dengan total indikasi kerugian negara Rp 256,3 miliar. Padahal, dana
sejumlah itu jika digunakan untuk melakukan intervensi pemulihan gizi buruk
anak balita yang dalam 90 hari membutuhkan Rp 1,5 juta per anak balita, bisa
menjangkau sekitar 170.000 anak balita.
Jumlah anak
balita penderita gizi buruk di NTT mencapai 60.616 dari total 504.900 anak
balita di sana. Ironis sekali ketika bantuan untuk mengatasi gizi buruk ataupun
rawan pangan yang digelontorkan pemerintah pusat dan lembaga donor lain belum
juga bisa membuahkan hasil positif, sementara di sisi lain ada indikasi korupsi
keuangan negara yang nilainya lebih dari dua kali lipat dari anggaran yang
dibutuhkan untuk penanganan seluruh kasus gizi buruk di sana.
Gambaran
lain, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir ada 587 surat pengaduan masyarakat
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaporkan indikasi tindak
pidana korupsi di NTT. Lebih dari seperempat kasus yang dilaporkan itu berada
di pusat pemerintahan NTT, yakni di Kota Kupang. Data KPK itu sejalan dengan
hasil survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2008 yang diselenggarakan
Tranparency International Indonesia (TII) yang menyebutkan Kupang sebagai kota
terkorup di antara 50 kota di Indonesia yang disurvei.
Dari hasil
telaah KPK, ada 13,46 persen pengaduan yang benar-benar terindikasi tindak
pidana korupsi dan diteruskan kepada penegak hukum. Masih ada pengaduan yang
dikembalikan ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan.
Indonesia
Budget Center (IBC), awal Mei lalu, mengutip hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) yang menyebutkan, pada semester II tahun anggaran 2009, terdapat
1.804 temuan pemeriksaan di NTT dengan 3.305 rekomendasi atas penyimpangan
anggaran daerah senilai Rp 5,29 triliun. Dari jumlah itu, ada 1.300 rekomendasi
yang nilai anggarannya mencapai Rp 2,06 triliun yang belum ditindaklanjuti.
Selain itu
juga ditemukan 392 kasus kerugian negara senilai Rp 76,45 miliar pada
penggunaan anggaran di NTT. Dari jumlah itu ada 280 kasus yang belum
ditindaklanjuti dengan pengembalian atas kerugian negara dengan nilai kerugian
Rp 58,08 miliar. Padahal, jika mengacu pada pagu pemberian beasiswa bagi siswa
SMA/SMK miskin di NTT tahun 2008 sebesar Rp 1,5 juta per orang dalam setahun,
kerugian negara sejumlah itu bisa digunakan untuk membiayai pendidikan bagi
hampir 13.000 siswa miskin hingga mereka tamat SMA/SMK.
Bencana
korupsi yang melanda NTT bisa dikatakan sudah cukup kronis. Pelakunya merasuk
dan tersebar di berbagai lapisan, mulai dari oknum pejabat pemda, pimpinan
proyek, entitas swasta, anggota DPRD, pengurus partai politik, camat, kepala
desa, bahkan hingga kepala sekolah dan guru (lihat Tabel). Aneh dan ironis saat
korupsi justru terjadi di daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin mencapai
1,01 juta jiwa atau sekitar 23,3 persen dari jumlah penduduk (2009).
Di level
kepala daerah, misalnya, mantan Bupati Ende Paulinus Domi dan mantan Sekretaris
Daerah Ende Iskandar Mberu ditahan karena terindikasi korupsi dana APBD Ende
2005 dan 2008 senilai Rp 3,5 miliar. Di luar itu, ada sejumlah mantan bupati
yang sempat tersangkut dugaan korupsi, yakni mantan Bupati Kupang Ibrahim
Agustinus Medah, mantan Bupati Rote Ndao Christian Nehmia Dillak, dan mantan
Bupati Timor Tengah Selatan Daniel Banunaek. Kasus Ibrahim dikabarkan telah
dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Daerah NTT, kasus Christian belum
diketahui kelanjutannya, sedangkan Daniel justru divonis tiga tahun penjara
atas pidana perambahan hutan.
Mantan Ketua
Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Larantuka Pastor Frans Amanue
mengungkapkan, filosofi otonomi daerah baik karena ingin mendekatkan pelayanan
publik. Namun, ekses yang muncul justru virus korupsi yang menyebar di
kabupaten hingga desa. Alokasi dana sulit diawasi.
Korupsi
menjalar ke seluruh lapisan penyelenggara pemerintahan karena tidak ada
tindakan hukum yang tegas kepada pelaku. Penegakan hukum perkara korupsi baru
sebatas pada tingkatan staf dan belum menyentuh ke pejabat di pemda.
Daya rusak
tindak pidana korupsi semakin terasa hebat karena sebagian mengakar hingga di
lingkungan sekolah dan guru. Parahnya lagi, belum ada tindakan hukum yang
menimbulkan efek jera bagi pelakunya ataupun bagi aparatur yang lain.
”Guru tidak
siap mengelola dana BOS (bantuan operasional sekolah) karena kurikulum di FKIP
(fakultas keguruan dan ilmu pendidikan) tidak mengajarkan itu. Masyarakat juga
belum banyak kritis mengawasi pengelolaan dana BOS,” kata anggota staf Divisi
Antikorupsi PIAR NTT, Paul SinlaEloE. Menurut dia, otonomi daerah dalam
pengelolaan dana dekonsentrasi pendidikan masih setengah hati.
Berdasarkan
pantauan PIAR NTT, 44 persen kasus dugaan korupsi berada di bidang
pemerintahan. Dari perspektif sektoral, 46,4 persen kasus korupsi ada di sektor
pengadaan barang dan jasa dari pemerintah, disusul sektor APBD (34,4 persen).
Tidak mengherankan jika muncul idiom baru dari NTT, yakni ”Nusa Tetap
Terkorup”.
Memang tak
semua pegawai di NTT terjangkiti virus korupsi. Di antara kubangan lingkungan
birokrasi yang korup, ternyata masih ada pegawai yang tidak mau memanfaatkan
kesempatan untuk korupsi meski secara ekonomi ia masih kekurangan. Salah
satunya Charles Daris (42), pegawai Dinas Koperasi Kota Kupang yang ditemui di
tepian pantai di Jalan Timor Raya, Kupang, Sabtu (8/5).
Saat itu ia
tengah berbincang dengan dua nelayan rekannya, Bonatus (62) dan Kornelis
Pulanga (42). Charles adalah pegawai negeri yang memiliki pekerjaan sambilan
sebagai nelayan. ”Pagi hari sampai siang, beta kerja kantor. Sore pukul 15.00
hingga 06.00 pagi, beta cari ikan di laut,” katanya.
Sebagai
pegawai golongan IID dengan gaji Rp 1,9 juta per bulan, tentu tidak akan
mencukupi kebutuhan bapak empat anak itu. ”Lebih baik beta kerja sambilan jadi
nelayan daripada beta harus korupsi,” katanya.
Sejak
diangkat menjadi pegawai tahun 1997, ia terus memegang jabatan bendahara. Baru
beberapa tahun terakhir ia melepas jabatan itu karena ingin lebih tenang.
”Kawan-kawan bilang, beta ini bendahara bodoh. Dari dulu sampai sekarang tidak
juga kaya, rumah itu-itu saja. Di sini, kalau jadi bendahara yang jujur itu
justru dibilang bodoh,” katanya lantas tertawa, diikuti dua rekan lainnya.
Andai
semua birokrat memiliki komitmen yang sama untuk tidak melakukan korupsi
seperti Charles, bisa jadi persoalan kemiskinan dan rawan pangan di NTT tidak
telanjur selaten saat ini. (KORNELIS
KEWA AMA - C Wahyu Haryo PS)
Sumber: Kompas, 25 Mei 2010.